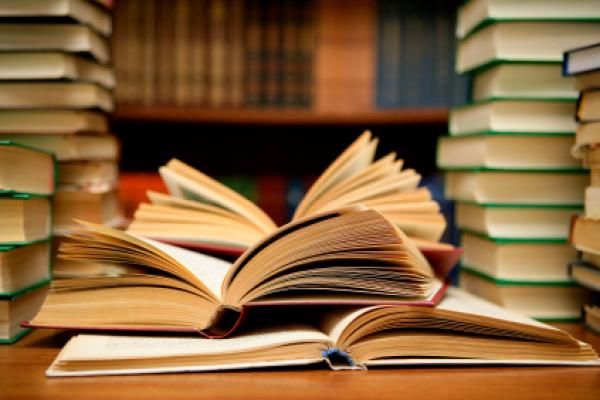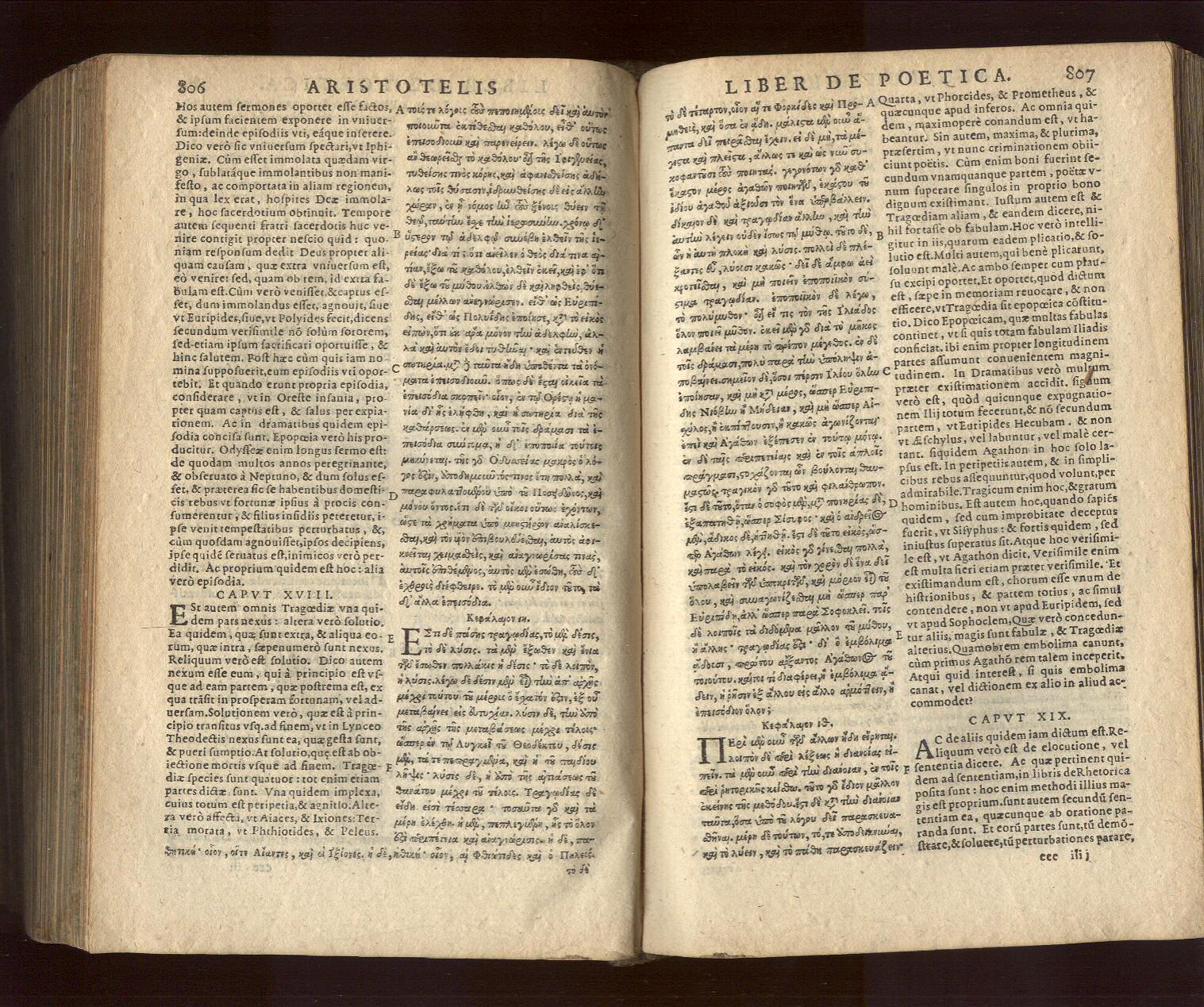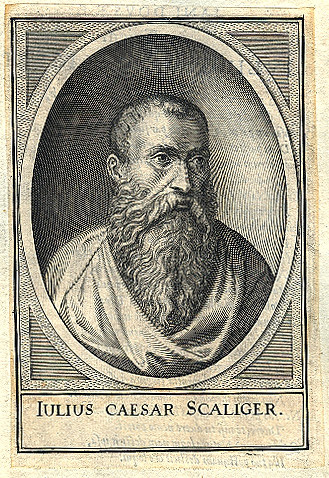RATU ISRAEL DAN JUDAH KUNO YANG ABADI:
PENAFSIRAN CERPEN “JEZEBEL” KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA
DENGAN PEMAHAMAN HERMENEUTIKA DILTHEY[1]
oleh
Indraswari
Pangestu (1206268150)
Hermeneutika—seperti yang dikatakan Palmer (1969) dan dikutip oleh Abdul
Hadi W.M. dalam bukunya yang berjudul Hermeneutika
Sastra Barat dan Timur (2014)—adalah teori penafsiran berkenaan dengan
permasalahan umum dalam memahami makna teks. Adapun, Mircea Eliade, dalam The Encyclopedia of Religion (1993),
mengartikan hermeneutika sebagai seni menafsir yang di dalamnya terdapat tiga
komponen penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu teks, penafsir, dan pembaca.
Dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah penafsiran sebuah karya yang
terkait dengan makna teks dan permasalahan umum.
Istilah hermeneutika pertama
kali diperkenalkan oleh Homerus, tetapi kemudian dipopulerkan oleh Plato dalam
bukunya yang berjudul Politikos,
Definitione, Ion, dan Timaeus[2].
Plato juga mengaitkan hermeneutika dengan spiritualitas sehingga sebuah teks
dapat terhubung dengan asas metafisika. Dalam esai ini, penulis membahas
tentang penafsiran cerpen “Jezebel” (1999) karya Seno Gumira Ajidarma yang
dikaitkan dengan kepercayaan spiritual bangsa Israel dan Judah Kuno. Penafsiran
tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dari Wilhelm
Dilthey (1957).
Ilmu hermeneutika berkembang pesat pada abad ke-19 saat Dilthey
menguraikan pemikirannya tentang penafsiran terhadap sebuah teks. Menurutnya,
untuk menafsirkan sebuah teks, seseorang harus mengikuti tiga tahapan penerapan
hermeneutika, yaitu (1) pengumpulan, pemilihan, dan penafsiran data, (2)
penelitian sejarah atau kesejarahan teks, serta (3) penyelesaian lingkaran
hermeneutik pemahaman[3].
Ketiga prinsip hermeneutika tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan cerpen
“Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma yang dikaitkan dengan keadaan historis dan
kepercayaan bangsa Israel dan Judah Kuno.
Cerpen “Jezebel” adalah salah satu cerpen karya Seno Gumira Ajidarma
yang tergabung dalam antologi cerpen Sepotong
Senja untuk Pacarku (2002). Kumpulan cerpen tersebut diterbitkan di Jakarta
oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Terdapat sebelas cerpen di dalam antologi
tersebut, termasuk “Jezebel” yang dituliskan Seno Gumira Ajidarma pada tahun
1999. Kesebelas cerpen yang terdapat dalam antologi tersebut memiliki latar
tempat pantai dan laut, serta latar waktu senja. Cerpen “Jezebel” pun bercerita
tentang seorang perempuan bernama Jezebel yang berjalan di tepi pantai pada
waktu senja. Seno Gumira Ajidarma menuliskan bahwa cerpen tersebut dikembangkan
dari dua buah lagu yang berjudul “Jezebel”, masing-masing dinyanyikan oleh
Edith Piaf dan Sade Adu[4].
Tuti Kusniarti, dalam artikelnya yang berjudul “Teks Sastra sebagai
Media Komunikasi Antarbangsa (Kajian atas Novel Dari Fontenay ke Magallianes Karya N.H. Dini)” (2010), menyatakan
bahwa makna karya sastra tidak bersifat tunggal, tetapi multi-interpretasi yang
akan mengungkapkan berbagai dimensi kekayaan teks yang bersangkutan. Hal
tersebut mendukung penulis untuk menafsirkan sebuah karya sastra. Dengan
demikian, penulis dapat memenuhi kaidah pertama hermeneutika Dilthey, yaitu
pengumpulan, pemilihan, dan penafsiran data. Data—seperti yang telah diuraikan
di atas—diambil dari cerpen Seno Gumira Ajidarma yang berjudul “Jezebel”. Dalam
hal ini, cerpen tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah karya sastra yang
menceritakan penggambaran hari akhir atau kiamat. Selain itu, cerpen tersebut
juga ditafsirkan sebagai sindiran terhadap suatu kepercayaan dan juga sindiran
terhadap jenis karya sastra eksperimentasi yang populer pada tahun 1970-an.
Kedua penafsiran tersebut didukung dengan data tambahan berupa terjemahan New Testament, Book of Revelations dalam
Kitab Injil, terjemahan surat “Al-Qariah” dalam Kitab Quran, terjemahan lagu
berjudul “Jezebel” karya Edith Piaf, terjemahan Book of Kings bangsa Israel dan Judah Kuno, serta artikel-artikel
mengenai keadaan jenis sastra eksperimentasi dan Indonesia. Pengumpulan
tambahan data tersebut dilakukan untuk mendukung analisis penafsiran terhadap teks.
Setelah pengumpulan, pemilihan, dan penafsiran data selesai dilakukan, hal yang
dapat dilakukan berikutnya adalah menganalisis kesejarahan teks.
Penafsiran mengenai penggambaran hari akhir atau kiamat dan sindiran
terhadap kepercayaan atau ekspremintasi tidak dilakukan tanpa pendukung. Kajian
pustaka historis dilakukan untuk mendukung penafsiran agar bersifat objektif.
Tafsiran penggambaran hari akhir atau kiamat dalam cerpen “Jezebel” karya Seno
Gumira Ajidarma didukung oleh terjemahan New
Testament, Book of Revelations dalam Kitab Injil dan terjemahan surat
“Al-Qariah” dalam Kitab Quran.
Dalam cerpen “Jezebel” tidak
disebutkan bahwa latar tempat dan waktu menggambarkan keadaan hari akhir. Akan
tetapi, deskripsi Seno Gumira Ajidarma memiliki kemiripan dengan deskripsi hari
akhir yang terdapat dalam Kitab Injil dan Kitab Quran. Cerpen “Jezebel” dibuka
dengan kalimat sebagai berikut.
Mayat-mayat
bergelimpangan di mana-mana sepanjang pantai itu [...] Berpuluh-puluh mayat,
beratus-ratus mayat, beribu-ribu mayat menghampar tak terbilang disiram ombak
yang berdebur dan menghempas dengan ganas bagai membantingkan sebuah pesan yang
paling kejam dan paling tak mengenal belas.
Deskripsi
naratif tersebut memiliki kemiripan dengan ayat keempat surat “Al-Qariah”. الْمَبْثُوثِ كَالْفَرَاشِ
النَّاسُ يَكُونُ يَوْمَ (101:4) ‘pada
hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran’[5].
Selain itu, keadaan dalam cerpen juga memiliki kemiripan dengan ayat ketiga bab
keenam belas Book of Revelation. And the second angel poured out his vial
upon the sea; and it became as the blood of a dead (man): and every living soul
died in the sea[6] (16:3) ‘dan
malaikat kedua menuangkan botol kecilnya ke laut; dan hal tersebut menjadikan
laut seperti darah mayat: dan setiap jiwa yang hidup lalu mati di laut’.
Keadaan mayat dalam cerpen “Jezebel”
karya Seno Gumira Ajidarma seperti menggambarkan keadaan manusia saat kiamat
yang terdapat Kitab Quran dan Kitab Injil. Mayat-mayat yang bergelimpangan di
sepanjang pantai adalah manusia yang bertebaran seperti anai-anai. Adapun mayat
yang dihempas ombak dengan ganas adalah dampak dari malaikat yang menuangkan
botol kecilnya dan menyebabkan kematian di laut. Cerpen “Jezebel” karya Seno
Gumira Ajidarma menggambarkan keadaan hari akhir yang diadaptasi dari
kitab-kitab.
Penafsiran berikutnya—tentang
sindiran terhadap suatu kepercayaan—didukung dengan adanya Book of Kings bangsa Israel dan Judah Kuno. Dalam Book of Kings diceritakan bahwa
perempuan bernama Jezebel adalah istri dari Ahab, Raja Israel Utara[7].
Menurut kepercayaan bangsa Israel dan Judah Kuno, Ratu Jezebel menghasut Raja
Ahab untuk berpaling dari Yahweh, Tuhan mereka di kala itu, untuk menyembah
Baal yang—dalam New Testament (Perjanjian
Baru)—lebih dikenal sebagai Beelzebub sang Iblis[8].
Jezebel lalu menganiaya nabi-nabi Yahweh dan menyebabkan kematian seorang
pemilik tanah yang tidak ingin menjual tanahnya kepada Raja Ahab. Hal tersebut
membawa Jezebel ke pengadilan. Ia kemudian dihukum mati dengan cara dilemparkan
dari jendela oleh para hakimnya. Setelah itu mayatnya dijadikan makanan untuk
anjing yang kelaparan. Terjemahan Book of
Kings tersebut menyatakan bahwa Jezebel adalah seorang Ratu Israel dan
Judah Kuno yang tidak disukai oleh rakyatnya karena suka menghasut untuk
menyembah Baal sang Iblis. Umat Yahweh kemudian mengutuk Ratu Jezebel dan
membunuhnya.
Dalam
lirik lagu Edith Piaf yang berjudul “Jezebel” pun, Jezebel dianggap sebagai
perempuan iblis. Lagu tersebut diakui Seno Gumira Ajidarma sebagai sumber
inspirasi penulisan cerpen. Hal tersebut ia tuliskan dalam bagian akhir cerpen
“Jezebel” dalam buku Sepotong Senja untuk
Pacarku[9].
Edith Piaf adalah penyanyi kabaret asal Prancis yang diakui sebagai diva
nasional Prancis dan bintang terbesar bagi rakyat Prancis[10].
Lagu “Jezebel” adalah lagu yang diciptakan oleh Wayne Shanklin dengan
menggunakan bahasa Inggris. Edith Piaf merekam versi bahasa Prancis dari lagu
tersebut pada tahun 1951. Dengan demikian, terdapat dua versi lirik pula,
pertama adalah lirik berbahasa Inggris dan kedua adalah lirik berbahasa Prancis.
If ever the devil was born,
Without a pair of horns
It was you,
Jezebel, it was you.
‘Jika sesosok
Iblis dilahirkan,
Tanpa mempunyai
sepasang tanduk
Ialah dirimu,
Jezebel, ialah
dirimu.’
Ce demon qui brulait mon coeur
Cet ange qui sechait mes pleurs
C'etait toi, Jezebel, c'etait toi[11]
‘Setan ini yang
membakar hatiku
Malaikat ini
yang mengeringkan air mataku
Itu
Anda, Jezebel, itu Anda’
Dalam lirik lagu tersebut tersurat bahwa Jezebel adalah setan. Dalam
bahasa Inggris, Jezebel digambarkan seperti jelmaan Iblis yang tidak mempunyai
tanduk. Adapun dalam bahasa Prancis, Jezebel digambarkan sebagai setan yang memainkan
hati manusia. Kedua terjemahan tersebut dapat menjadi data pendukung sindiran
yang terdapat dalam cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma. Sindiran
tersebut adalah sindiran yang dilemparkan kepada umat Yahweh atau Israel dan
Judah Kuno.
Sindiran terhadap umat Yahweh terjadi ketika Jezebel dalam cerpen
“Jezebel” digambarkan sebagai satu-satunya makhluk yang masih hidup di muka
bumi ketika kiamat terjadi. Hal tersebut seakan menyatakan bahwa Ratu Jezebel,
sang penyembah Iblis, adalah satu-satunya makhluk yang benar. Artinya, dengan
menyembah Baal, Jezebel diberikan keabadian, sedangkan manusia-manusia lain
yang tidak menyembah Baal diberikan kematian.
“Aku lelah,”
katanya (Jezebel) kepada angin, “siapa yang tidak lelah berjalan tanpa henti
sepanjang pantai menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan? Tapi aku tidak bisa
berhenti meskipun aku sudah hampir tidak kuat lagi. Harus ada yang setidaknya
melihat mayat-mayat itu. Harus ada yang sekadar menghormatinya. Kalau tidak,
siapa yang akan melakukannya? Tiada lagi manusia yang masih tersisa di muka
bumi ini. Aku sendirian tak mungkin mengubur mereka semua, bahkan untuk
menengoknya pun barangkali seluruh waktu hidupku tidak akan pernah cukup.
Pantai ini tidak ada ujungnya dan mayat-mayat bertebaran sepanjang pantai tak
terbilang. Harus ada yang sekadar menengoknya meski tidak bisa berbuat apa-apa,
meskipun semuanya sudah punah. Tinggal aku sendiri di dunia menjalani ziarah
yang panjang ini, yang tak akan pernah cukup untuk duka kehidupan di muka
bumi.”
Potongan
paragraf di atas dapat ditafsirkan sebagai sindiran untuk umat Yahweh. Bangsa
Israel dan Judah Kuno dianggap melakukan kesalahan karena pada akhirnya hanya
Ratu Jezebel yang dapat hidup abadi dan dapat menyaksikan kematian manusia yang
tidak menyembah Baal. Sindiran terhadap suatu kepercayaan seperti ini tidak
saja dilakukan oleh Seno Gumira Ajidarma (entah Seno Gumira Ajidarma melakukan
sindiran dengan sengaja atau tidak). Akan tetapi, A.A. Navis sudah lebih dulu
melakukan sindiran kepada umat Islam dengan cerpen “Robohnya Surau Kami”
(1956). Selain itu, sindiran terhadap umat Kristen dan Katolik juga dilakukan
oleh Dan Brown dengan bukunya yang berjudul The
Da Vinci’s Code (2003). Dalam cerpen “Robohnya Surau Kami”, Navis menyindir
umat Islam dengan mengatakan bahwa seorang haji yang taat beribadah kepada
Allah akan tetap masuk neraka jika tidak berbakti kepada bangsa. Adapun, Dan Brown
menyindir umat Kristen dan Katolik dengan mengatakan bahwa Yesus memiliki
keturunan dari hasil persetubuhannya dengan seorang pelacur bernama Maria
Magdalena.
Sindiran lain
yang dapat ditafsirkan dari cerpen “Jezebel” adalah sindiran terhadap keadaan jenis
eksperimentasi sastra Indonesia. Maman S. Mahayana, dalam bukunya yang berjudul
Kitab Kritik Sastra (2015),
mengatakan bahwa ketika tahun 1970-an sastra Indonesia dilanda semangat
eksperimentasi, sejalan dengan gerakan “kembali ke akar, kembali ke tradisi”.
Pada tahun-tahun tersebut, sastra Indonesia seakan meninggalkan
“kebarat-baratannya” dan bergeser untuk menonjolkan budaya Indonesia.
Karya-karya beraliran filsafat Barat seperti karya-karya Iwan Simatupang mulai
digantikan dengan karya-karya Kuntowijoyo dan Gus Mus yang dikaitkan dengan
spiritualitas mistik Jawa dan tasawuf.
Aliran filsafat Barat digantikan dengan kepercayaan Jawa dan Islam. Keberadaan
cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma yang ditulis pada tahun 1999 seakan
ingin “mengajak” kembali para penikmat sastra Indonesia untuk menikmati aliran
Barat. Oleh karena itu, cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma dapat ditafsirkan
sebagai sindiran untuk menyudahi eksperimentasi budaya Jawa dan Islam.
Berakhirnya
pemaparan mengenai keadaan sejarah dan penafsiran data cerpen “Jezebel” menandakan
bahwa kaidah ketiga hermeneutika Dilthey juga telah diterapkan. Dilthey
menyebutkan bahwa kaidah terakhir hermeneutikanya adalah penyelesaian lingkaran
hermeneutik pemahaman. Prinsip pemahaman Dilthey tersebut diakhiri dengan
proses imajinatif pemahaman[12].
Artinya, dalam membaca karya sastra, pembaca terpanggil untuk membangun
pengalaman kembali tentang manusia secara imajinatif dan menghubungkan
pengalaman kejiwaan yang disajikan karya dengan pengalaman pembaca yang
diperoleh dalam pembelajaran tentang sejarah dan lain sebagainya[13].
Usaha penyambungan kutipan dalam cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma
dengan keadaan sejarah telah menuntaskan penyelesaian lingkaran hermeneutik
pemahaman. Pengalaman kejiwaan yang didapatkan dari membaca cerpen “Jezebel”
membuat penafsir teringat kepada penggambaran hari kiamat yang terdapat dalam
Kitab Injil dan Kitab Quran. Setelah itu penafsir dapat mengembangkan proses
imajinatif pemahaman dengan melakukan lebih banyak kajian pustaka historis
terhadap teks.
Sebagai sebuah
cerpen yang menggambarkan keadaan hari akhir atau menyindir kepercayaan suatu
umat, tentu Seno Gumira Ajidarma bukanlah orang pertama yang telah
menuliskannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, cerpen “Robohnya Surau
Kami” karya Navis pun sudah menggambarkan keduanya terlebih dulu pada tahun
1956. Dalam hal ini, Ajidarma kehilangan unsur inovasi. Akan tetapi, usahanya
untuk menyindir eksperimentasi tahun 1970-an Indonesia menjadi hal yang patut
dilihat kembali. Cerpen “Jezebel” seakan mengatakan, “sudah cukup,” kepada
model karya sastra eksperimentasi yang mengadaptasi kebudayaan Jawa ataupun
Islam. Seno Gumira Ajidarma mengembalikan minat “kebarat-baratan” dengan
mengadaptasi sebuah lagu asal Prancis dan cerita asal Israel.
Sebuah karya
sastra dapat diinterpretasikan dengan bebas oleh pembaca. Akan tetapi,
penafsiran yang bersifat pribadi cenderung membuahkan interpretasi karya sastra
yang subjektif. Kritik sastra harus memberikan kritik yang objektif. Demi
menghindari penafsiran subjektif, dibutuhkan data-data pendukung kesejarahan
teks yang mengobjektifkan interpretasi. Penafsiran yang telah dilakukan penulis
terhadap cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma adalah penafsiran dengan
cara hermeneutika Dilthey. Dalam hermeneutika Dilthey, pembuktian kesejarahan
menjadi pendukung terpenting untuk menafsirkan suatu karya sastra. Dengan
demikian, penulis dapat menggunakan hermeneutika Dilthey untuk menafsirkan
cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma sebagai cerpen yang menggambarkan
keadaan hari kiamat, menyindir kepercayaan suatu umat, dan menyindir keadaan
eksperimentasi sastra Indonesia.
Daftar
Acuan
Ajidarma,
Seno Gumira. 2002. Sepotong Senja untuk
Pacarku “Jezebel” (1999). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Book of
Revelation. Diakses dari http://www.discoverrevelation.com/Rev_16.
Dilthey,
Wilhelm. 1957. Das Erlebnis und die
Dichtung: Lessing Goethe, Novalis, Hoerderlin. Gottingen: Vandenbeck &
Ruprecht.
Eliade,
Mircea. 1993. The Encyclopedia of
Religion. Macmillan Reference Books.
html,
pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.08 WIB.
Huey, Stev.
"Edith Piaf: Biography". Yahoo!
Music. Diakses pada tanggal 3 September 2009.
Indeks
Al-Qur’an Hadits Online: Database Surat Ayat Al-Qur’an Hadits dan
Terjemahannya. Diakses dari http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/11/al-quran-dan-terjemahan-surat-101-al.html,
pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 00.57 WIB.
Knowles,
Elizabeth. 2006. "Jezebel". The Oxford Dictionary of Phrase and
Fable, OUP.
Kusniarti,
Tuti. 2010. “Teks Sastra sebagai Media Komunikasi Antarbangsa (Kajian atas
Novel Dari Fontenay ke Magallianes Karya
N.H. Dini)”. Jurnal Bahasa dan Seni, Volume 11, Nomor 1, tahun 2010.
Lyrics
Translate. Diakses dari http://lyricstranslate.com/en/jezebel-jezebel.html-2,
pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.44 WIB.
Palmer,
Richard E. 1969. Hermeneutics:
Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer.
Evanston: Northwestern University Press.
Toorn, K.
v. d., Becking, B., & Horst, P. W. v. d. 1999. Dictionary of Deities and Demons in the Bible DDD (2nd extensively rev.
ed.) (154). Leiden; Boston; Grand Rapids, Mich.: Brill; Eerdmans.
W.M., Abdul
Hadi. 2014. Hermeneutika Sastra Barat dan
Timur. Jakarta: Sadra International Institute.
[1]
Esai Kritik Sastra,
dikumpulkan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah Kritik Sastra
Indonesia, Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, tahun ajaran 2014/2015.
[2]
Diambil dari Abdul Hadi W.M..
2014. Hermeneutika Sastra Barat dan Timur.
Jakarta: Sadra International Institute. Halaman 33.
[4]
Seno Gumira Ajidarma. 2002. Sepotong Senja untuk Pacarku. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
[5]
Diambil dari Indeks Al-Qur’an Hadits Online: Database Surat
Ayat Al-Qur’an Hadits dan Terjemahannya. Diakses dari http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/11/al-quran-dan-terjemahan-surat-101-al.html,
pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 00.57 WIB.
[6]
Diambil dari Book of Revelation. Diakses dari http://www.discoverrevelation.com/Rev_16.html,
pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.08 WIB.
[8]
Toorn, K. v. d., Becking, B., & Horst, P. W. v. d. 1999. Dictionary of Deities and Demons in the Bible DDD (2nd extensively rev. ed.) (154).
Leiden; Boston; Grand Rapids, Mich.: Brill; Eerdmans.
[9]
Seno Gumira Ajidarma, op. cit., halaman 30.
[11]
Diambil dari Lyrics Translate. Diakses dari http://lyricstranslate.com/en/jezebel-jezebel.html-2,
pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.44 WIB.
[12]
Abdul Hadi W.M., op. cit., halaman 105.